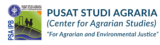Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan

Pembaruan Agraria Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan
 Istilah Pembaruan Agraria (Agrarian Reform), sekalipun telah menjadi kata kunci dalam perdebatan di sekitar pembangunan di banyak negara sejak 1950-1965-an (tidak terkecuali Indonesia), namun hingga saat ini istilah tersebut masih saja sering disalah maknai, bahkan ironisnya masih banyak komponen masyarakat yang tidak memahaminya. Mengacu pada UUPA 1960, Setiawan (1997) mendefinisikannya sebagai “upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam merubah hubunganhubungan sosial agraria dan bentuk-bentuk penguasaan tanah dan sumberdaya alam ke arah keadilan dan pemerataan, melalui mekanisme dan sistem politik yang demokratis dan terbuka bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Sementara Ghimire (2001) memaknai pembaruan agraria sebagai “…suatu perubahan penting di dalam struktur agraria, yang berdampak pada peningkatan akses penduduk miskin pedesaan atas tanah, serta kepastian penguasaan tanah bagi mereka yang secara nyata mengerjakan tanah/ penggarap. Di dalamnya termasuk akses pada input pertanian, pada pasar serta jasa-jasa dan dukungan yang diperlukan”
Istilah Pembaruan Agraria (Agrarian Reform), sekalipun telah menjadi kata kunci dalam perdebatan di sekitar pembangunan di banyak negara sejak 1950-1965-an (tidak terkecuali Indonesia), namun hingga saat ini istilah tersebut masih saja sering disalah maknai, bahkan ironisnya masih banyak komponen masyarakat yang tidak memahaminya. Mengacu pada UUPA 1960, Setiawan (1997) mendefinisikannya sebagai “upaya-upaya yang dilakukan oleh negara dan masyarakat dalam merubah hubunganhubungan sosial agraria dan bentuk-bentuk penguasaan tanah dan sumberdaya alam ke arah keadilan dan pemerataan, melalui mekanisme dan sistem politik yang demokratis dan terbuka bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Sementara Ghimire (2001) memaknai pembaruan agraria sebagai “…suatu perubahan penting di dalam struktur agraria, yang berdampak pada peningkatan akses penduduk miskin pedesaan atas tanah, serta kepastian penguasaan tanah bagi mereka yang secara nyata mengerjakan tanah/ penggarap. Di dalamnya termasuk akses pada input pertanian, pada pasar serta jasa-jasa dan dukungan yang diperlukan”
Dalam praktiknya program pembaruan agraria yang dijalankan ternyata sangat bergantung pada sistem ekonomi politik dan watak rezim pemerintahan yang berkuasa, sehingga terdapat berbagai ragam model dan pola pelaksanaan pembaruan agraria. Pada masa Orde Lama, nampak adanya ide-ide dasar pembaruan agraria yang lebih didasarkan pada redistribusi tanah yang menyeluruh (Land Reform). Sementara menjelang masa berkuasanya Orde Baru, ide-ide semacam itu sepertinya mulai ditinggalkan dan diganti oleh modernisasi pertanian dengan program terkenalnya “revolusi hijau”. Hasil dari dekade “pembangunan tanpa pembaruan agraria“ tersebut, menunjukkan banyaknya terjadi kegagalan, terutama tercermin dari meluasnya disparitas pendapatan dan semakin meluasnya kemiskinan pada masyarakat desa yang dijauhkan dari akses produktif mereka. Seperti disinyalir Hutagalung (1985) bahwa, “Sesudah 20 tahun pelaksanaan program ini, secara keseluruhan tujuannya belum tercapai. Beribu-ribu orang yang tidak mempunyai tanah menguasai tanah secara illegal dan pola pemilikan tanah menunjukkan suatu kegagalan program redistribusi tanah”.
Dan kini, ketika era Otonomi Daerah (desentralisasi) di Indonesia mulai digulirkan pada 1999, yang ditandai dengan hadirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diamandemen dengan UU No. 32 Tahun 2004, setidaknya telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk “mengurus“ daerahnya sendiri. Pemerintahan daerah diberikan tanggung-jawab besar untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat1. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya