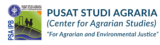Perizinan dalam Institusi PSEUDO-LEGAL: Serpihan Kisah Nyata GNPSDA-KPK

Oleh: Prof. Hariadi Kartodihardjo (Guru Besar IPB, Dewan Pendiri Pusat Studi Agraria IPB)
“Lebih baik menyalakan lilin, daripada mengutuk kegelapan” (HTW, 2017)

Institusi korupsi dapat mendesign perilaku orang-orang yang sama sebagai abdi negara juga jaringannya, tetapi bukan seperti apa yang dimaksud oleh peraturan-perundangan. Terdapat penambahan pemain, selain abdi negara dan pengusaha sebagai subyek utama, yaitu orang dan lembaga sebagai konsultan atau perantara maupun adanya eminent persons.
Pemain dari luar pemerintah itu bukan hanya bertugas menyelesaikan syarat-syarat perizinan—yang juga membuat sub-kontrak pekerjaan kepada konsultan lain, tetapi juga dapat menjadi mediator antara pengusaha dan abdi negara, apabila keduanya memerlukan sesuatu.
Institusi Pseudo—Legal
Relasi semacam itu terbangun di dalam institusi korupsi sebagai “institusi kembaran” dari institusi formal, yang justru bisa menjadi nafas kehidupan lembaga negara yang sesungguhnya. Relasi yang dibentuk oleh institusi kembaran itu memecah pelaksanaan pemerintahan menjadi dua urusan yang menjadi satu kesatuan.
Pertama, urusan formal sebagai bentuk pelaksanaan tugas negara sebagaimana mestinya. Dalam hal ini menggunakan segala bentuk simbol-simbol pemerintahan resmi seperti kop surat, ruang rapat, honorarium dari APBN/APBD, dlsb. Kedua, urusan pelayanan dan hubungan dengan masyarakat yang dilipat menjadi urusan personal antara pejabat, konsultan dan pengusaha. Oleh karena itu mengapa dalam judul disebut “pseudo—legal” karena institusi itu berbentuk hybrid antara legal dan extra-legal.
Dapat bertahannya institusi demikian itu selama puluhan tahun, menunjukkan bahwa dari berbagai sisi—finansial, hukum, manajemen, juga moralitas—layak berjalan; dengan kata lain, semua bentuk dan macam resiko dapat ditanggung. Segala sesuatu yang berjalan dalam waktu lama seperti itu menguntungkan bagi pelakunya. Kalau merugikan dan menyesatkan, pasti berhenti dengan sendirinya tanpa diminta orang lain.
Korupsi Perizinan
Dari dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD) 2016, diketahui bahwa dalam satu tahun di suatu pemerintahan propinsi, kabupaten dan kota yang jumlah semuanya 539, masing-mssing terdapat sekitar 76 sampai 194 investasi yang memerlukan studi AMDAL atau UKL/UPL. Itu artinya di Indonesia setiap tahun tidak kurang dari 40.964 studi lingkungan dilakukan, belum termasuk di Pusat.
Dalam pertemuan di KPK yang membahas inisiatif swasta dalam pengendalian korupsi tahun lalu, disebutkan bahwa dalam satu tahun potensi uang suap di seluruh Indonesia sekitar Rp 51 Trilyun yang terkait dengan perizinan. Dan angka itu termasuk dalam proses penilaian dan pengesahan dokumen AMDAL.
Dokumen-dokumen lingkungan sebagai persyaratan perizinan seperti AMDAL, lebih memenuhi manfaat sebagai persyaratan administrasi, namun secara umum tindak lanjut implementasinya lemah. Juga terdapat kasus, dokumen itu dapat tersusun tanpa harus disusun oleh ahli-ahlinya. Bahkan ada dokumen AMDAL dan perizinan yang secara administrasi sah, tetapi sesungguhnya semua dokumen administrasi itu palsu.
Hal demikian itu menyebabkan tingginya kecepatan pembangunan di berbagai bidang, yang terkait dengan hak-hak atas tanah, ijin-ijin pelepasan kawasan hutan atau penggunaan kawasan-kawasan lindung yang dilarang, mudah terdapat kasus pelanggaran. Apabila hal itu semua dilihat secara keseluruhan dalam bentuk “gambar besar”, maka tujuan kebijakan lingkungan hidup, kesejahteraan maupun keadilan sosial sudah digembosi dari dalam, sejak awalnya.
Itu artinya, tanpa membenahi korupsi perizinan, upaya-upaya yang dilakukan seperti sertifikasi, verifikasi legalitas, maupun instrumen-instrumen CSR, dana desa, moratorium, perhutanan sosial maupun reforma agraria ibarat pelaksanaan “minus malum” atau second best. Bahkan instrumen seperti one-map dapat terhenti karena keterbukaan informasi perizinan tidak mungkin bisa diwujudkan ketika masih terjadi korupsi perizinan.
Masalah Orang dan Sistem
Bersama kawan-kawan Libang KPK dalam riset maupun diundang oleh segenap orang, telah mendapat informasi bagaimana manipulasi proses perizinan itu terjadi. Fakta-fakta seperti: manipulasi peta, pemerasan dengan atau tanpa mengatas-namakan atasan, tawaran tambahan atau pengurangan luas izin yang dimohon sebagai alat negosiasi, biaya pengesahan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan, memperlambat proses dengan penggunakan pasal-pasal karet, menyimpangkan proses misalnya tidak melalui BKPM/D atau melalui unit kerja satu-pintu tetapi ongkos transaksinya sama saja, adanya konsultan sebagai arena transaksi yang sudah ditunjuk oleh pejabat tertentu, diuraikan satu per satu kasus-kasusnya.
Namun demikian, apabila dicermati lebih jauh, jelas pula dapat diidentifikasi bahwa persoalannya tidak selalu harus ditujukan pada perorangan ataupun kelompok, tetapi juga ada persoalan lemahnya sistem perizinan dan regulasi sebagai penyebabnya. Diketahui setidaknya ada tiga jenis regulasi yang mungkin menjadi penyebab, yaitu: systemic corruptive regulations, criminogenic regulations, serta vulnerable corruptions.
Jenis yang pertama dapat menyebabkan kerugian negara secara langsung maupun tidak langsung atau ada design kelompok tertentu diuntungkan dan yang lain dirugikan. Jenis yang kedua, dapat menyebabkan kondisi jebakan yangmana siapapun yang bekerja cenderung akan melakukan korupsi. Jenis yang ketiga, menyebabkan adanya kesempatan yang terbuka, sehingga mendorong adanya perilaku oportunis.
Namun demikian, sebaik-baik regulasi, senantiasa ada celah korupsi apabila terdapat situasi eksklusif dalam sistem perizinan itu. Pengalaman GNPSDA-KPK selama ini juga menunjukkan, apabila tidak ada penindakan, agenda-agenda pencegahan tidak berjalan dengan baik, kecuali terdapat kepemimpinan yang kuat.
Maka, walaupun dengan berat hati narasi ini dibuat, karena harus mengungkap aib, harapannya tidak lagi ada rahasia umum. Sebaliknya sudah menjadi pengetahuan terbuka yang harus disikapi. Dan dari situ terdapat kesadaran pentingnya mencegah terjadinya korupsi perizinan, yang punya dampak buruk sangat luas. Lebih baik menyalakan lilin, daripada mengutuk kegelapan (HTW, 2017).